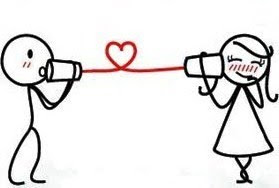28 Februari 2010
Beberapa hari yang lalu saya datang ke acara pengukuhan guru besar seorang dosen di fakultas saya. Beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa, meraih gelar doktor pada usia yang sangat muda, dan diangkat menjadi professor di awal empat puluhan. Belum lagi beliau adalah seorang wanita, muslim, sudah menikah dan punya tiga orang anak.
Kurang apalagi coba?
Kebahagiaan memang tidak bisa diukur. Tidak dengan jabatan, tidak dengan kekuasaan, apalagi dengan uang.
Mungkin begitu juga dengan beliau. Beliau, yang di tengah pidato pengukuhannya, meneteskan air mata saat mengucapkan terimakasih kepada almarhum ayahandanya.
Tapi bukan itu yang menarik perhatian saya. Yang menarik perhatian saya adalah, saat beliau mengucapkan rasa terima kasihnya kepada suaminya, yang diucapkan hingga dua kali oleh beliau. Yang pertama memang tertulis di buku pidato pengukuhan guru besarnya, hanya saja yang kedua....
“kepada suamiku tercinta, mohon maaf atas segala kesalahanku selama ini, semoga engkau terus berkenan membimbingku ,menerimaku, menemaniku hingga akhir perjalanan hidupku...”
(--maaf agak diedit karena penulis tidak ingat dengan sempurna)
Saya ingin menangis. Saya ingin menangis karena, entah mengapa saya merasa, dibalik segala pencapaian karir yang telah beliau peroleh, segala penelitian yang telah beliau selesaikan, ternyata beliau hanyalah seorang—wanita—biasa. Beliau adalah seorang istri, ibu dari tiga orang anak. Yang harus melayani suami dan mengurus anak-anaknya. Bukannya bagaimana sih, tapi ntah bagaimana sepertinya saya mengetahui, beban yang beliau tanggung.
Karena sesulit apapun di tempat kerja, selalu ada anak-anak yang menelpon minta diperhatikan.
Secapek apapun dari tempat kerja, akan selalu ada suami yang minta disiapkan teh di sore hari.
Dan sesukses apapun karir di tempat kerja, saat keluarga sedang ada masalah, terutama dengan anak-anak, ibu lah yang akan disalahkan.
Menjadi wanita, berkarir dan berkeluarga, tidak akan pernah mudah.
Saya ingat seorang ibu mengomentari ibu lainnya, “ih kok anaknya nggak rangking ya di kelas, padahal ibu bapaknya sarjana, S2 lagi.”
Oh, Tuhan.